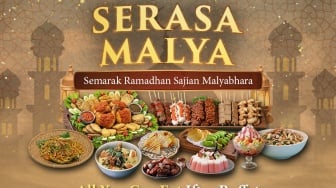SuaraJogja.id - Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah belum lama ini ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.
Makin banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi pun mendorong Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) untuk menggelar Diskusi Seputar Korupsi (Diksi) #9 bertema "Kepala Daerah dalam Lingkaran Korupsi", Jumat (5/3/2021).
Dalam diskusi tersebut, salah satu yang disoroti Peneliti Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar adalah biaya politik mahal, yang membuat para kandidat di pilkada memutar otak untuk balik modal.
Zainal pun membeberkan "kecerdasan" seorang kepala daerah berlatar belakang pengusaha yang tak ia sebutkan identitasnya.
Baca Juga:KPK Sita Uang Rp 1,4 Miliar, Nurdin Abdullah : Itu Bantuan Untuk Masjid
"Dia sudah menang dalam pilkada, tinggal menunggu dilantik, jadi dia belum sebagai kepala daerah, pejabat negara, tapi yang dia lakukan adalah, dia kumpulkan semua rekanan, pengusaha-pengusaha, lalu dia suruh kumpul uangnya. Dia bilang, "Kumpul sekarang juga, kalau Anda tidak bayar, saya jaminkan untuk lima tahun mendatang, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari proyek-proyek di daerah,"" jelas Zainal.
Kasus ini dinilainya menarik karena bisa membingungkan KPK, mengingat pengusaha tersebut belum menjabat kepala daerah atau penyelenggara negara, sehingga unsur pasal-pasal yang berlaku dalam hukum di Indonesia tak bisa disangkakan padanya.
"Itu saking cerdasnya untuk korup, dia bisa mengkreasikan dengan sedemikian rupa, dan seingat saya, KPK cukup kebingungan ketika mau menyusun delik yang akan dikenakan pada orang itu," tutur dia.
"Kepala daerah itu canggih-canggih, banyak yang bermenteal, berotak sudah mencari uang secara sangat luar biasa," tambahnya.
Dalam contoh kasus Nurdin Abdullah sendiri, Zainal menyebutkan, memang Nurdin Abdullah adalah tokoh elite di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, yang ia pimpin selama 10 tahun sejak 2008 sebelum menjadi gubernur Sulsel. Bahkan, keluarga elite di Bantaeng tunduk padanya.
Baca Juga:Ditahan Sejak Akhir Februari, Nurdin Abdullah Baru Diperiksa KPK Hari Ini
"Tapi begitu dia pindah ke Sulawesi Selatan, dia menghadapi di mana dia hanya kelas satu di antara sekian banyak elite, dan itu membuat dia harus berakomodasi. Dia harus mengakomodir kepentingan-kepentingan itu," kata dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (HTN FH) UGM itu.
Zainal melanjutkan, sempat ada upaya pemakzulan Nurdin Abdullah dari DPRD Sulsel sekitar delapan bulan setelah ia dilantik sebagai gubernur.
"Akhirnya dia lepas dari itu setelah melakukan upaya-upaya politik," terang Zainal.
Dirinya menilai, ada faktor umum dan faktor khusus di balik praktik korupsi di daerah. Faktor umum, kata dia, antara lain pemilu berbiaya mahal, kualitas individu, hingga ketidakmampuan membangun pengawasan.
Sementara itu, faktor khusus dalam kasus Nurdin Abdullah berasal dari sang koruptor sendiri, yang berkaitan dengan akomodasi politik.
"Dia harus mengakomodir kepentingan-kepentingan berbagai klan dan kekuatan-kekuatan besar di Sulawesi Selatan," jelas Zainal.
Terkait pemilu, yang berbiaya mahal hingga mendorong kandidat untuk melakukan korupsi, Zainal menyebutkan, perlu adanya perbaikan sistem pemilihan, aturan, sampai penegakannya.
Kondisi biaya politik mahal ini juga diamini Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kendati begitu, ia menggarisbawahi ketidakjujuran peserta pilkada saat melaporkan dana kampanye.
Berdasarkan kajian KPK, Titi menerangkan, kandidat kepala daerah membutuhkan biaya rata-rata Rp20 miliar hingga Rp30 miliar untuk maju sebagai bupati/wali kota dan bisa ratusan miliar untuk calon gubernur dalam pilkada.
Namun kenyataannya, dalam laporan dana kampanye calon para kepala daerah yang dipublikasikan KPU di situs resminya, tak ada angka sebesar itu.
"Anomalinya adalah, yang disebutkan itu selalu politik biaya tinggi, tetapi ketika kita ingin mengkonfirmasi melalui mekanisme formal, data yang kita dapat adalah data yang seperti ini," kata Titi.
Ia menambahkan, ada ketidakjujuran dalam laporan dana kampanye karena sumbangan yang diterima tidak semua dilaporkan. Bahkan, lanjutnya, berdasarkan temuan di tahun-tahun sebelumnya, KPK sendiri sudah dengan sangat lugas memaparkan bahwa "calon menyerahkan sejumlah uang kepada partai politik, namun tidak dilaporkan sebagai penerimaan dana partai politik."
Titi pun menyayangkan, hingga kini belum ada solusi konkret yang ditawarkan meskipun sudah diketahui secara gamblang permasalahan soal korupsi oleh politisi.
Namun, untuk permasalahan korupsi calon kepala daerah yang belum dilantik -- sebelumnya diungkapkan Zainal, Titi menawarkan dua opsi: LHKPN harus dilaporkan calon kepala daerah meskipun bukan pejabat negara dan tindak pidana korupsi juga bisa ditegakkan pada calon pejabat negara.
Sementara itu, narasumber lainnya, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) UGM Mada Sukmajati, mengungkapkan siklus korupsi politisi yang ia kutip dari seorang politikus PDI Perjuangan.
Di tahun pertama, ia menjelaskan, pemenang pilkada akan mengembalikan modal, lalu mencari untung di tahun kedua dan ketiga, diikuti akumulasi modal untuk pemilu berikutnya pada tahun keempat dan kelima, supaya terpilih lagi.
"Pak Nurdin itu terpilih [sebagai gubernur] di Pilkada 2018 ya kalau enggak salah. Ini mungkin sudah tidak return of capital ini, sudah tidak mau mengembalikan modal, tapi sudah fase profit taking, profit seeking, ngambil untung dulu di tahun kedua dan ketiga," ujar Mada.
Senada dengan Zainal, Mada menilai, para politikus memang pandai mencari celah untuk melakukan korupsi, bahkan, kata dia, sejak awal dilantik.
"Mungkin bahkan ketika mengucapkan sumpah pelantikan itu di dalam otaknya mungkin sudah berniat korupsi, jadi mulutnya mengucapkan sumpah janji jabatan pada Allah dan seterusnya, tapi otaknya sudah mikir, nanti setelah dilantik, apa yang bisa dikorup," ungkap Mada.