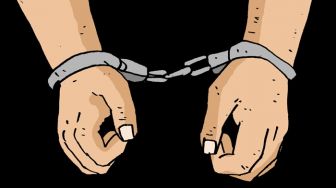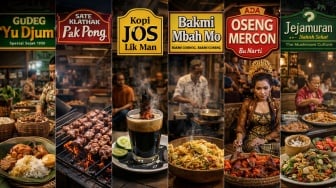- Aksi penangkapan oleh aparat polisi semakin banyak saat ini
- Dugaan keterlibatan aktivis sebagai penghasut atas kerusuhan besar saat Demo DPR di beberapa kota
- Metode Jakarta pun kembali mengemuka saat ini bagaimana aparat menangkap tanpa prosedur yang jelas
SuaraJogja.id - Gelombang penangkapan aktivis sosial dan mahasiswa oleh aparat kepolisian akhir-akhir ini memicu kekhawatiran serius terhadap kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Kasus-kasus seperti penangkapan Muhammad Fakhrurrozi (Paul) dari Social Movement Institute (SMI), Delpedro Marhaen dari Lokataru, hingga staf Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNY, Perdana Arie Veriasa, menyoroti dugaan praktik penangkapan tanpa prosedur yang jelas dan kurangnya transparansi dari pihak berwenang.
Fenomena ini, yang kian mencuat pasca demonstrasi DPR pada 27-31 Agustus 2025, mengundang perbandingan dengan metode represi di masa lalu dan menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas aparat di era modern.
Gelombang Penangkapan Aktivis dan Mahasiswa: Pembungkaman Demokrasi di Era Digital
Baca Juga:Mahasiswa UNY Ditangkap Terkait Demo, Keluarga dan Pengacara Keluhkan Kurangnya Transparansi Polisi
Penangkapan aktivis Paul di Yogyakarta pada Sabtu, 27 September 2025, menjadi salah satu sorotan utama.
Menurut Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Dhanil Alghifary, Paul ditangkap di kediamannya pada pukul 14.35 WIB oleh puluhan orang dengan sepeda motor dan dua mobil, beberapa di antaranya mengenakan baju gelap dan ada pula yang berseragam Satpol PP.
Paul dipaksa masuk ke dalam mobil tanpa surat keterangan penangkapan dan langsung dibawa ke Polda Jawa Timur, sehingga LBH Yogyakarta tidak mendapatkan surat resmi penangkapan.
Keluarga dan kuasa hukum Paul tidak mendapatkan pemberitahuan yang jelas mengenai penangkapannya.
Tak kalah mengkhawatirkan adalah kasus Perdana Arie Veriasa, mahasiswa dan staf BEM UNY, yang ditangkap oleh Polda DIY pada Rabu, 24 September 2025.
Baca Juga:Penangkapan Aktivis Paul di Jogja: Kronologi Detail, dari Pria Misterius hingga Dugaan Penghasutan
Penangkapan ini diduga terkait dengan rangkaian aksi demonstrasi di Polda DIY akhir Agustus lalu, dengan Arie disangkakan tuduhan pengerusakan fasilitas umum di bawah Pasal 170, 187, atau 406 KUHP.
Tim hukum Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (BARA ADIL) menyoroti adanya dugaan tindakan kekerasan atau ketidaksesuaian prosedur saat penangkapan, serta kurangnya transparansi kepada keluarga dan kuasa hukum.

Pemberitahuan kepada keluarga terlambat, baru disampaikan setelah penangkapan berlangsung.
Kasus Direktur Lokataru Foundatiom, Delpedro Marhaen, disebutkan sebagai bagian dari pola penangkapan aktivis tanpa prosedur yang jelas.
Pihak aparat diyakini menuding akun-akun media sosial yang digunakan atau dimiliki para aktivis ini sebagai sumber dan penghasut massa yang melakukan pengrusakan di sejumlah kota saat Demo DPR.
Tuduhan ini mengindikasikan adanya dugaan keterikatan aktivis terhadap kelompok tertentu, dan upaya untuk membungkam narasi yang menyampaikan kebenaran atas kemunduran demokrasi di Indonesia.
Bayang-bayang Metode Jakarta: Represi dari 1965 ke 2025
Pola penangkapan yang mengedepankan asosiasi sosial daripada bukti tindakan nyata ini mengingatkan pada "Metode Jakarta" yang diterapkan pada tahun 1965.
Istilah yang dipopulerkan oleh Vincent Bevins ini merujuk pada kekerasan massal di Indonesia pada tahun 1965, di mana jutaan orang dicurigai komunis dan dihukum tanpa bukti pidana, hanya berdasarkan asosiasi mereka.
Pada masa Orde Baru, daftar nama disusun oleh aparat lokal, laporan RT, arsip organisasi, hingga kartu anggota koperasi, menjadi dasar untuk penangkapan massal, penghilangan, dan penyingkiran individu.
Logika 'bersalah karena asosiasi' (guilty by association) ini menutup ruang bagi warga untuk membela diri, mengubah identitas, bacaan, dan pergaulan menjadi pasal pidana.
Di era modern, "Metode Jakarta" ini menemukan bentuk barunya melalui kriminalisasi yang lebih rapi, terutama dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial.
Tindakan sederhana seperti mengikuti (follow), membagikan ulang (repost), berkomentar, atau sekadar kedekatan sosial di dunia maya, bisa menjadi alasan penangkapan.
Jejak digital dikompilasi menjadi semacam basis data terselubung yang digunakan aparat untuk bergerak cepat, seringkali tanpa bukti pidana yang nyata.
Efek jangka panjang dari metode ini sangat merusak.
Kepercayaan antarwarga terkikis, membuat orang ragu untuk berteman, membaca buku kritis, atau bergabung dalam lingkaran diskusi politik.
Solidaritas yang seharusnya menjadi fondasi masyarakat demokratis justru diubah menjadi risiko.
Aparat juga kerap melakukan "teater barang bukti," di mana buku, zine, atau poster politik dipamerkan sejajar dengan benda tumpul seperti batu atau botol, seolah-olah memiliki daya ledak yang sama.
Hal ini menciptakan narasi publik yang menghubungkan asosiasi visual dengan ancaman, padahal belum tentu mengarah pada tindakan kriminal.
Fenomena anonimitas massal dalam penangkapan juga kembali terulang. Dengan hampir 4000 orang ditangkap dan 959 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, mayoritas tidak dikenal publik, mempersulit upaya membangun solidaritas dan tekanan politik.
Mencermati Kembali Sejarah: Kekejaman PKI dan Konteks Represi
Untuk mendapatkan pandangan yang berimbang, penting untuk juga mencermati kekejaman yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu.
Pada peristiwa 1965, PKI dituduh sebagai dalang di balik Gerakan 30 September (G30S) yang mengakibatkan pembunuhan enam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat.
Selain itu, dalam sejarahnya, PKI juga terlibat dalam pemberontakan Madiun 1948 yang menewaskan sejumlah kiai, santri, dan tokoh masyarakat lainnya.
Tragedi ini menjadi luka mendalam bagi bangsa Indonesia dan menjadi salah satu alasan utama di balik trauma kolektif terhadap komunisme, yang pada gilirannya memicu operasi penumpasan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya.
Namun, meskipun kekejaman PKI diakui secara historis, hal itu tidak dapat membenarkan praktik represi yang tidak transparan atau melanggar prosedur hukum, yang justru berpotensi menimbulkan kesalahan penangkapan dan mencederai keadilan.
Akuntabilitas Aparat dan Tantangan Penegakan Hukum

Dari sudut pandang akademik, upaya aparat dalam menindak dalang kericuhan di beberapa kota yang justru mengarah pada aktivis LSM, mahasiswa, dan pemilik akun media sosial dengan prosedur yang tidak jelas adalah sebuah ironi.
Penegakan hukum yang tidak transparan dan cenderung represif hanya akan memperburuk kondisi demokrasi dan kebebasan sipil.
Penangkapan tanpa surat perintah, penggunaan kekerasan, dan penundaan pemberitahuan kepada keluarga dan pengacara, seperti yang terjadi pada Paul dan Pradana Arie, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip due process of law.
Jika yang ditangkap bukan orang yang dimaksud atau bukti yang disangkakan tidak kuat, Polri tentu harus mempertanggungjawabkannya.
Kurangnya transparansi dalam proses hukum, dari penangkapan hingga penetapan tersangka, membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam sistem hukum yang adil, setiap individu berhak atas bantuan hukum, informasi mengenai tuduhan yang dikenakan, dan proses peradilan yang transparan.
Besar kemungkinan Polri dapat dituntut balik oleh para aktivis yang ditangkap jika terbukti ada pelanggaran prosedur hukum dan hak asasi manusia dalam penangkapan dan penahanan mereka.
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan tidak dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dan disita kecuali atas perintah tertulis yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang sah menurut undang-undang.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menjadi dasar bagi gugatan praperadilan atau gugatan perdata atas kerugian yang diderita.
Lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendampingi para korban dan menuntut akuntabilitas aparat.
Pada akhirnya, pola represi yang berulang ini, dari "Metode Jakarta" di masa lalu hingga manifestasi digitalnya hari ini, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.
Penting bagi aparat penegak hukum untuk kembali pada prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan transparansi, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.